Gren Mahe, keunikan sebuah Budaya
WARGA Kampung Boganatar, Desa Kringa, Kecamatan Talibura, memiliki budaya unik yang biasa digelar dalam sebuah pesta budaya. Budaya tersebut bernama Gren Mahe.
 Gren Mahe, merupakan pesta adat menyambut kemenangan terhadap berbagai tantangan. Ritual adat ini sebenarnya sudah ditinggalkan sejak 22 tahun silam, tanpa satu alasan yang pasti. Dan, selama jangka waktu terlupakannya ritual tersebut, masyarakat di wilayah ini tertimpa berbagai tantangan dalam interaksi sosialnya. Antara lain terserangnya berbagai sumber penyakit, kekeringan, menurunnya produktivitas pertanian dan lainnya.
Gren Mahe, merupakan pesta adat menyambut kemenangan terhadap berbagai tantangan. Ritual adat ini sebenarnya sudah ditinggalkan sejak 22 tahun silam, tanpa satu alasan yang pasti. Dan, selama jangka waktu terlupakannya ritual tersebut, masyarakat di wilayah ini tertimpa berbagai tantangan dalam interaksi sosialnya. Antara lain terserangnya berbagai sumber penyakit, kekeringan, menurunnya produktivitas pertanian dan lainnya.Seharusnya ritus adat ini dilakukan setiap lima tahun sekali. Dan, dirayakan dalam sepekan sejak pembangunan Woga dan pembersihan Namang sebagai lokasi upacara.
Pada dua hari perayaan ini, selain dihadiri seluruh warga Kampung Boganatar juga warga dari desa tentangga di ufuk Timur Kabupaten Sikka yakni Desa Hikong dan Timutawa.
Bapak Yosef Moses, salah seorang tokoh dan pemangku adat setempat menuturkan bahwa terakhir pesta budaya ini dilaksanakan pada tahun 1985 atau 22 tahun silam. Ia sendiri tidak merinci apa alasannya.
Moat Moses mengatakan, makna pelaksanaan ritus ini adalah untuk meminta berkat dari Ibu Bumi atau Ina Nian Tana dan Bapa Langit atau Ama Lero Wulan Reta agar bumi, Kampung Boganatar dan masyarakat di wilayah ini senantiasa diberi kedamaian, sukses dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan berbudaya, dikaruniai persaudaraan dan jauh dari konflik.
"Ancaman wabah penyakit dan gagal panen juga merupakan ujud pesta budaya ini. Warga, melalui para kepala suku dan Ata Moan Weta Naruk (= pembawa doa dan syair adat) Moan Dego, akan menyampaikan doa-doa tersebut kepada leluhur dan wujud tertinggi atau Amapu," katanya.
Selain itu, ritus budaya ini juga dimaksudkan untuk meminta hujan dan siklus musim yang teratur, memohon kesuburan tanah, serta keselamatan serta membangun tekad warga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Puncak acara Gren Mahe hari pertama tanggal 12 November adalah ritus Tudi-Laba. Pada prinsipnya melui ritus ini para kepala suku yakni suku Wulo, Ketang Kaliraga dan Lewar Lau Wolo memohon restu para leluhur dan sang Pencipta agar seluruh acara gren mahe berlangsung sukses.
Mereka juga memanjatkan doa kepada leluhur dan Tuhan agar para petugasnya diberi kebijakan dalam setiap kesempatan rembuk dan dialog serta pemanjatan doa kepada leluhur dan Yang Maha Tinggi dalam tiga termin doa, yakni pujian, syukur dan permohonan. Acara Tudi-Laba berlangsung di rumah kepala suku di Kampung Boganatar yang berjarak lebih kurang dua kilometer dari lokasi gren mahe di bukit Natar Nuhu.
Rangkaian acara berikutnya adalah perarakan hewan korban dari Kampung Boganatar menuju bukit Natar Nuhu, lokasi gren mahe. Hewan korban utama yakni Widin Tanah bersama hewan korban lainnya diarak kaum pria dalam tari-tarian dan pekik kemenangan. Dengan dandanan lesu rajan dan sarung/sa'en mereka didoakan untuk selalu tampil perkasa baik dalam mengarak hewan korban, maupun selama ritus berlangsung dan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Di tengah pawai dan arak-arakan itu sesekali terdengar seruan kemenangan Ha' Iaaa.. Seruan tersebut mencerminkan ciri maskulinitas dari perayaan ini sebagai perayaan kemenangan. Nuansa kemenangan itu dimaknai sebagai kemenangan atas berbagai hal yang dapat mencederai kehidupan masyarakat.
Tiba di lokasi gren mahe, para pengiring disambut hentakan musik gong-waning. Rangkaian acara berikutnya adalah pemindahan Keris Tawa Tana ke dalam Woga di lokasi gren mahe. Rangkaian acara hari pertama berakhir dengan acara malam jaga yang diisi dengan tari-tarian hingga pagi.
Pada hari kedua, rangkaian pesta budaya ini diawali dengan acara Witi Watu Wara Mahang. Watu Wara Mahang jenis batu ceper atau batu piring yang diambil dan diarak dari arah matahari terbit oleh tiga kepala suku dilanjutkan dengan penanaman Watu Marang pada Mahe oleh seorang tokoh adat yang diangkat oleh para kepala suku dan diberi jabatan "Moan Marang" atau panglima adat.
Jeda acara selama lebih kurang satu jam dari pukul 12.00 - 13.00 wita diisi dengan tari-tarian oleh seluruh hadirin.
Pesta rakyat dan ritus Gren Mahe dilanjutkan dengan pemotongan 15 ekor hewan korban, di antaranya Widin Tanah yang didandani tipa, sejenis selendang yang telah berusia puluhan tahun.
Acara ini menjadi moment paling menegangkan. Rakyat bersorak-sorai memberi semangat kepada hadirin yang mendapat mandat dari para kepala suku untuk melakukan pemotongan hewan korban. Putra Tana Ai yang mendapat mandat untuk memotong satu ekor hewan korban melakukan ritual. Masyarakat bertempik sorak memberi dukungan kepada anak tana, memotongan seekor kambing dengan sempurna disambut tarian dan kahe (sorak-sorai) para hadirin.
Daging hewan korban selanjutnya dibagikan kepada para hadirin disertai emping yang disebut Pelang atau Pare Pelang menandai perjamuan persaudaraan sekaligus mengakhiri pesta budaya ini.
Sumber : http://www.inimaumere.com/2010/12/gren-mahe-keunikan-sebuah-budaya.html
DINAMIKA KEBUDAYAAN SUKU DAYAK NGAJU
Suku Dayak Ngaju merupakan salah satu anak suku terbesar yang mendiami pulau Kalimantan. Suku Dayak Ngaju memiliki 4 suku sedatuk dan 90 suku sefamili. Suku-suku tersebut baik suku sedatuk maupun suku sefamili, masing-masing memiliki bahasa derahnya masing-masing.
Ngaju berarti udik. Hal ini mungkin karena suku Dayak Ngaju menempati daerah sungai yang berada di udik dibandingkan suku-suku Dayak lainnya. Suku Dayak Ngaju mendiami sepanjangan daerah aliran sungai Kapuas, sungai Kahayan, bahkan sekarang banyak yang mendiami kota Palangkaraya dan kota Banjarmasin.
Suku Dayak Ngaju adalah suku termaju yang menyebar di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pada umumnya masyarakat suku Dayak Ngaju memeluk agama Kristen Protestan yang dibawa masuk oleh misionaris Zending Barmen dan Basel . Namun ada juga yang masih memegang keyakinan asli suku dayak yaitu Kaharingan (Hindu Kaharingan) dan ada juga yang memeluk agama Kristen Katolik dan Islam.
Pusat kemajuan atau peradapan suku Dayak Ngaju terdapat di kota-kota:
1. Banjarmasin (ibukota provinsi Kalimantan Selatan)
2. Kuala Kapuas (ibukota kabupaten Kapuas, di aliaran sungai Kapuas)
3. Mandomai (ibukota kecamatan Kapuas Barat kabupaten Kapuas, di aliran sungai Kapuas)
4. Kuala Kurun (ibukota kabupaten Gunung Mas, di aliran sungai Kahayan)
5. Tewah (ibukota kecamatan Tewah, kabupaten Gunung Mas, di aliran sungai kahayan)
6. Pangkoh
1. Banjarmasin (ibukota provinsi Kalimantan Selatan)
2. Kuala Kapuas (ibukota kabupaten Kapuas, di aliaran sungai Kapuas)
3. Mandomai (ibukota kecamatan Kapuas Barat kabupaten Kapuas, di aliran sungai Kapuas)
4. Kuala Kurun (ibukota kabupaten Gunung Mas, di aliran sungai Kahayan)
5. Tewah (ibukota kecamatan Tewah, kabupaten Gunung Mas, di aliran sungai kahayan)
6. Pangkoh
Mayarakat suku Dayak Ngaju di daerah ini banyak generasi mudanya yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dari jenjang SMA, SGA, bahkan ada pula ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri sekalipun.
SISTEM RELIGI/KEPERCAYAAN
Sistem religi masyarakat Suku Dayak pada umumnya dan suku Dayak Ngaju pada khususnya merupakan kepercayaan yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan, menguasai dan memelihara alam semesta berserta isinya
Pada zaman dulu, masyarakat suku Dayak memeluk agama Helu atau Kaharingan. Agama Kaharingan merupakan salah satu agama etnis di nusantara, yang saat ini telah mendapat pengakuan dari Pemerinta Indonesia sebagai suatu agama, agama Hindu Kaharingan. Namun hal ini belum banyak diketahui dan dikenal oleh banyak masyarakat lainnya di Indonesia, bahkan banyak yang salah duga dengan mengira agama Kaharingan sebagai agama kafir dan penyembah berhala. Dalam perkembangannya, Kaharingan juga bersentuhan dengan agama besar lainnya di Indonesia namun tradisi asli Dayak masih sangat kental dalam pelaksanaan ritual keagamaannya.
Agama Kaharingan atau Helu merupakan kepercayaan asli suku Dayak yang berasal dari kata haring artinya hidup. Menurut kepercayaan pemeluk agama Kaharingan, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu namun sejak awal penciptaan, sejak Tuhan yang disebut Ranying Hatalla menciptakan manusia. Ranying berarti Maha Tunggal, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Jujur, Maha Lurus, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Suci, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Adil, Maha Kekal dan Maha Pendengar. Hatalla berarti Maha Pencipta.
Di zaman penjajahan, baik masa penjajahan Belanda mapun Jepang, perkembangan keyakinan Kaharingan banyak mengalami tekanan dan hambaran. Kehadiran penjajah mengalami kontradiksi serta sakit hati yang dalam hingga masih berdampak sampai saat ini dan masih terasa juga dialami oleh orang Dayak.
Para penjajah pada masa ini tidak mau memahami keyakinan yang dipeluk oleh orang Dayak. Dengan gamblang para penjajah menyatakan agama Helu atau Kaharingan yang menyembah Ranying Hattala dengan murni, polos, alami dan apa adanya sesuai dengan situasi alam, pemahaman dan cara berpikir suku Dayak, sebagai agama kafir, agama heiden, penyembah berhala, dan berbagai tuduhan lainnya. namun walaupun dengan tuduhan dan cemoohan dari para penjajah, mereka tetap mengizinkan orang Dayak utnuk melaksanakan upacara adat yang wajib mereka laksanakan.
Kemudian agama Kristen mulai masuk dibawa oleh lembaga-lembaga Zending yang merupakan missionaris di seluruh pulau Kalimantan. Dengan usaha pendekatan yang cukup lama dan perlahan tapi pasti, orang Dayak mulai membuka hati dan tertarik dengan keyakinan yang diperkenalkan oleh Zending. Kemudian, dari rasa ingin tahu yang besar tersebut kemudian banyak orang Dayak yang belajar tentang ajaran Kristen dan akhirnya memeluk agama Kristen.
Orang Dayak yang memeluk agama Kristen diwajibkan untuk membuang jauh-jauh kehidupan lamanya dulu serta memutuskan hubungan dengan adat istiadat dan tradisi suku, apapun yang berhubunfan dengan kebudayaan asli milik mereka yang sudah turun temurun, baik yang positif maupun negatif harus ditinggal jauh-jauh. Hal ini yang menyebabkan orang Dayak yang menjadi Kristen dari generasi berikutnya tidak lagi mengenal budaya dan asal usulnya secara kental. Namun, perkembangan saat ini dari generasi muda yang melanjutkan pendidikan dan hidup di perantaua mulai mencari asal dari rasa kehilangan atas budaya leluhurnya.
Orang Dayak yang memeluk agama Kristen diwajibkan untuk membuang jauh-jauh kehidupan lamanya dulu serta memutuskan hubungan dengan adat istiadat dan tradisi suku, apapun yang berhubunfan dengan kebudayaan asli milik mereka yang sudah turun temurun, baik yang positif maupun negatif harus ditinggal jauh-jauh. Hal ini yang menyebabkan orang Dayak yang menjadi Kristen dari generasi berikutnya tidak lagi mengenal budaya dan asal usulnya secara kental. Namun, perkembangan saat ini dari generasi muda yang melanjutkan pendidikan dan hidup di perantaua mulai mencari asal dari rasa kehilangan atas budaya leluhurnya.
Kemudian, saat agama Islam berkembang di bagian Indonesia lainnya, maka agama Islam pun masuk ke pulau Kalimantan. Orang Dayak yang kemudian memeluk agama Islam dengan resmi menyatakan dirinya sebagai orang Melayu, sejak masa penjajahan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan asal usul sukunya tidak terdengar lagi, walaupun secara tidak langsung/secara batin mereka masih merasa sebagai suku Dayak. Secara umum suku Dayak dan suku Melayu terpisah kerana disebabkan sistem kepercayaan dan pergaulan sosial.
Sekitar tahu 1967-an, di Kalimantan Tengah, orang Dayak yang menganut agama Kaharingan hanya sejumlah 30% dan sisanya menganut agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam.
Sumber : http://www.isenmulang.com/mitos-budaya/dinamika-kebudayaan-suku-dayak-ngaju
Sumber : http://www.isenmulang.com/mitos-budaya/dinamika-kebudayaan-suku-dayak-ngaju


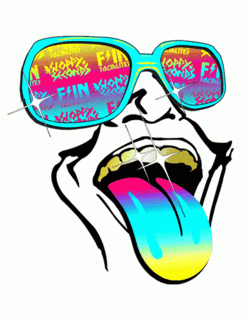
 ANGALIMANGCITY
ANGALIMANGCITY


